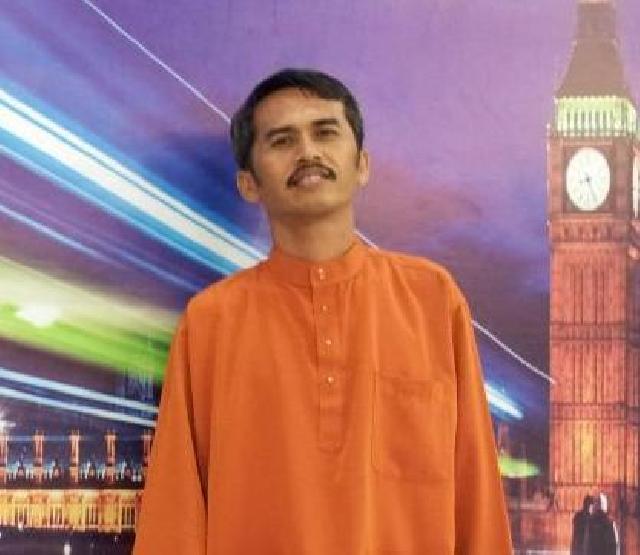Masih dalam ingatan semasa kecil dulu di kampung halaman tercinta, tepatnya di Kenegerian Pangean Kuansing, dimana dikala bapak pergi “mararuah” ke hutan, kami penuh harap agar beliau pulang cepat sorenya, karena beliau berangkat sewaktu subuh disaat kakinya bergelut dengan “acek” karena suasana hutan waktu itu adalah hutan basah dan sangat nyaman sekali untuk dinikmati, seperti berada di tengah gedung “panggarogau langik” yang ber-ayiaar kondisen- dengan suhu 14’c. Sayapun pernah suatu ketika diajak bapak ke hutan, dengan memakai baju panjang lengan, dan “salowar” yang ujungnya telah diikat dengan “kojai”, dengan rmaksud agar acek tidak menyatu dan menggigit dengan menghisap darah tubuh kita, seperti pejabat korup yang ada saat ini yang telah meluluh lantakkan ekonomi negara kita.
Kenapa kami harap penuh rasa penasaran menunggu bapak pulang dari hutan ? karena melihat apa yang bakal dibawa bapak dari hutan, suatu hal yang pasti membawa bermacam-macam buah-buahan, “buah tampui, cupak, garabinti, kayu kolek, buah rotan”, bahkan kabau saudaranya jengkol, sampai ke petaipun dibawa bapak dari hutan, bahkan kadangkala bapak membawa kancil, kijang atau rusa hasil tangkapannya bersama kerabatnya yang sama-sama pergi kehutan, pokoknya dikala bapak pulang dari hutan, bisa kita bayangkan pada saat ini, bagaikan pulang dari pasar cik puan jika kita berada di Kota Pekanbaru ini. Membawa semua kebutuhan sehari-hari bahkan seminggu dan sebulan kedepan, betapa indahnya hidup dikala jaman itu, hutan adalah gudang mencari nafkah, hutan adalah sumber segala kehidupan kami sekampung dan senegeri. Hutan merupakan laboratorium kehidupan bagi masayarakat kuantan sewaktu itu, rasanya sedih dan selalu berkabung kami dengan kehidupan pada saat kemerdekaan ini, kata beberapa tokoh masyarakat yang sudah tua renta yang telah hidup tiga zaman, penjajahan, yakni penjajah dan penjajah serta penjajahan abad ini.
Namun semua itu hanyalah tinggal kenangan yang tak perlu diratapi lagi karena semua itu sudah berubah menjadi lain sama sekali, bahkan cerita ini akan jadi dongeng dan cerita mau tidur bagi anak cucu kita nantinya bahkan. Kerkemungkinan sekarang sudah menjadi cerita dongeng bagi sebagian para pembaca sekalian. Walaupun sewaktu itu bapak dan “mondek” kita juga menebang dan menebas, namun mereka masih mempunyai perasaan yang penuh dengan tanggung jawab bersama, selalu mempunyai naluri menanam dan menanam dengan tanaman yang sama atau berbeda. Bahkan kalau mengambil kayu besar di tengah hutan untuk pembuatan jalur (lomba pacu jalur nasional), selalu dengan etika memohon dan meminta pada sang penguasa rimba yakni Allah SWT agar diberikan berkah dan kemapunan jika mereka berbuat salah.
Dulu kala nenek monyang bahkan saya sendiri masih ikut merasakan, bagaimana romantisnya kehidupan kala itu. Masih segar dalam ingatan kami, jika makan rambai bahkan kadang kala buah rambutan, tampangnya (biji) cendrung kami telan, dengan maksud apabila terasa mau buang air besar, maka kami berlari-lari ke “palak” atau ke pinggiran hutan untuk buang hajat, karena umumnya buang air besar kita diikuti oleh biji-bijian buah yang kami makan, karena tak terrolah dengan baik oleh lambung kita. Alhasil biji yang dibuang via anus tersebut akan tumbuh jadi bibit baru lagi, untuk melanjutkan kelangsungan hidup buah-buahan tersebut, dimasa yang akan datang untuk generasi penerus.
Demikianlah arifnya orang tua kita waktu itu, dimana ‘guncirik’pun bisa diajak menanam dan menanam sekaligus jadi pupuk organic tanaman yang kaya akan unsure nitrogennya, menakjubkan sekaligus membahayakan juga jika kita bawa pada saat ini yang kita tidak ternbiasa dengan kebiasaan local tersebut. Dan ini tak mesti pula kita contoh dalam kehidupan saat ini, namun tujuan saya hanyalah ingin menjelaskan bahkan tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat waktu itu sangat tinggi tanpa pamrih harus mendapatkan adi pura ataupun adipati yang berpura pura, pura bersih tapi punya sikap yang kotor, menghalalkan segala cara.
Kesimpulannya bahwa Masyarakat sekitar hutan cukup arif dan bijaksana dalam mengelola hutannya. Sebagai contoh kasus ditempat lain atau di Riau sendiri, Suku Sakai, Bonai, Petalangan dan suku lainnya yang ada di Indonesia, cukup arif dan bersahaja memelihara hutan dan sebatang pohon. Menebang pohon dianggap kesalahan terbesar kedua setelah membunuh manusia, dimana ketika sebatang pohon ditebang warga demi untuk kepentingan pribadi maka warga tersebut didenda, bahkan jika tanaman tersebut sudah berumur panjang dan tua maka tanaman tersebut dibungkus dengan kain putih, sebagai pertanda penghormatan pada pohon tersebut.
Makanya di Kuansing sewaktu kayu besar akan diambil untuk keperluan jalur, maka semua orang sekampung pergi menebang pohon tersebut dengan membawa orang pintar sebagai penghormatan pada pohon yang akan ditebang tersebut, dan waktu dan harinya untuk menebangpun ditentukan harinya. Dengan mantera yang dibaca yang intinya meminta pada Allah SWT, agar tanaman ini akan tumbuh lagi penggantinya, dan dimohonkan keselamatan dikemudian hari bagi anak cucunya. Sedikit saya nukilan materanya; “Oo..penguaso rimbo.. nen tinggal di sakek antuang, nen iduik di solo-solo tanah, nen iduik di tanah-tanah maninggi, kami nak mambuek jaluar, bori izin kami untuak menobang kayu iko, jangan bori kami penyakik poniang, paliharo la kami go, barokat kulimah Laillah haillallah…”
Demikianlah sekelumit penggalan mantera yang dibacakan Pawang piawai sebelum menebang kayu jalur. Makna di atas bukan berarti Orang Kuansing menganut aninisme, karena Tuhan adalah Esa adanya “Qul huwa Allahu ahad” tetapi mantera tersebut mencerminkan bahwa Masyarakat Kuansing sangat menghargai keberadaan semua makhluk ciptaan Tuhan, mereka tak ada tapi berada, mereka tak terlihat tapi kasat. Demikianlah hakikinya pemberian penghargaan pada makluk sesama ciptaan Tuhan, namun semua kalimat mantera tersebut di atas, dibuncal dengan kalimat akhir yang paling agung tiada Tuhan selain Allah, hanyalah kepada Allah kami meminta.
Dalam sebuah nukilan sejarah pembuatan jalur ini dijelaskan bahwa, pertama kali jalur diadakan di Rantau Kuantan sejak abad 20, jalur yang aslinya dulu mempunyai panjang 25-30 m dengan lebar 1,5 m, dengan muatan pemacunya sebanyak 40-65 orang. Dibuat dari pohon besar yang liat tapi ringan, berserat halus tapi tak lapuk, lurus tapi tidak tirus tak berlubang tapi tak bertingkah. Dengan besaran lingkaran sepemelukan 4 orang dewasa, tumbuh di tanah yang berani, pohon yang ber-roh, bermambang akarnya, batangnya dan bermambang pula pada pucuk daunnya.
Rimba Memakai Hukumnya
Kemudian beberapa perusahaan besar datang yang menyebabkan semua kenangan diatas hanyalah tinggal kenangan yang akan dinikmati oleh anak cucu dimasa yang akan datang, akibatnya Yang kaya pengusaha dan oknum penjabat dan menanggung beban adalah masyarakat setempat. Apalagi yang berkedok memakai HPH yang melahirkan kerusakan sumber daya hutan dan marginalisasi masyarakat, rusaknya sumber daya hutan, degradasi keanekaragaman hayati, banjir berketerusan dan longsor, Kasus 2002-2003 beberapa tahun yang lalu, terjadi 5 (lima) kali banjir besar berturut-turut, Hasil survey Greennomics, Walhi, ATTR di 7 (tujuh) kabupaten,
Akibatnya yang dialami masyarakat adalah kerugian langsung 876 M – APBD Riau 2002 1,3 Triliun, sedangkan kerugian tak langsung adalah berupa sakit yang dialami masyarakat setempat, bagkan kematian pun sering terjadi sebagai akibat penyakit yang diderita bahkan pengaruh langsung dari air yang dalam tersebut, ibarat kata orang Kuansing “tacobuar ka bondar, dicatuak dek ular, la taurak salowaaaar” ada juga berupa konflik-konflik yang berkepanjangan sampai saat ini.
Penyebab dari semua ini juga akibat tidak jelasnya pengakuan terhadap tanah ulayat apalagi selama jaman orde baru yang mengaburkan makna tanah ulayat, padahal pada Era Soekarno UU Agraria no. 60 / 1960 keberadaan ulayat diakui dengan cukup jelas, namun mulai pada era Soeharto UU no. 5/1967 tidak diakui lagi, dan bahkan sekarang keluar lagi Pepres baru tahun 2005, lebih parah lagi tidak hanya tanah ulayat yang tidak diakui bahkan tanah milik sendiripun sudah agak kabur makna kepemilikannya, disaat digunakan untuk kepentingan public, tetapi semoga saja hal seperti tidak terjadi pada pemilikan harta benda kita, bahkan anak dan isteri kita.
Akhirnya jika mencari kambing hitam tentulah banyak yang akan didapatkan, tetapi saat ini semua nasi telah menjadi bubur bahkan semua kayu dihutanpun telah menjadi bubur bagi perusahaan besar yang bergerak dibidang bubur kertas ini, sekarang yang penting bagaimana kita membina yang ada, membuat mitra yang saling menguntungkan kita semua, mengurangi dampak yang timbul dari semua petaka yang mungkin akan muncul, bisa saja petaka langsung sebagai akibat musnahnya hutan basah seperti di Kenegerian Pangean yang saya katakan tadi, banjir berkelanjutan seperti temuan Grenomic, bahkan konflik-konflik yang terjadi dengan perusahaan dan sesama warga masyarakat, dan terjadinya degradasi sumber daya alam bahkan juga berdampak terjadinya degradasi moral yang dibawa pendatang (perusahaan) bermukim para germo dan wanita penghibur yang berada sekitar lingkaran perusahaan saat ini.
Semua ini perlu disikapi bersama, perlu suatu penelitian dan kajian yang mendalam, model seperti apa yang akan kita lakukan untuk pembinaan ini, syukur alhamdulillah pihak perusahaan sudah mempunyai konsep yang jelas sehingga mari kita bekerjasama menerapkan di lapangan, sehingga kambing hitam tidak bergentayangan di mana-mana, mari kita putih-sucikan kambing hitam tersebut. Apalagi kita barusan melepaskan hari raya qurban, hari raya korban dengan menemukan kambing putih yang suci, kita sembelih semua keserakahan nafsu binatang yang diperlambangkan oleh kambing putih tersebut, sehingga nafsu syahwat merusak hutan, membabat hutan basah tanpa perasaan manusiawi.
Perbuatan tersebut sama saja halnya dengan membunuh manusia di Riau ini secara perlahan, karena hutan masa lalu merupakan laboratorium kehidupan, sekarang hutan tersebut sudah mulai terhancurkan oleh perkembang industry yang kataya untuk devisa negara namun meninggalkan derita bagi anak cucu kita, semoga kedepan akan lebih baik lagi dalam menata hutan kehidupan, bukan hutan garapan akasiah, karena ketika kita menanam maka disaat itulah kita berfikir dalam beberapa tahun akan ditebang, suatu penghijauan yang merisaukan kita semua. Mari kita tanam pohon dalam rangka melestarikan lingkungan yang berkelanjutan.
Ir. Mardianto Manan, MT
Ketua ForDas Riau